
Recovery Pendidikan Agama yang Dekontekstual
BLA (BLA Semarang) Semarang menghelat seminar “Pendidikan dan Revivalisme Islam di Indonesia”, Rabu 18 Mei 2020. Bertempat di Convention Hall Prof. Soherto UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, seminar ini dihadiri oleh Dr. Samidi, M.S.I., (BLA Semarang) Dr. AJi Sofanudin (Pusat Riset Ilmu Sosial dan Humaniora BRIN), dan Prof. Irwan Abdullah (UGM).
Seminar ini mengkaji eksistensi lembaga pendidikan kuttab yang bercorak revivalis Islam. Pembahasan kuttab kali ini dikontekstualisasikan dengan kondisi pendidikan kontemporer serta lahirnya paham keagamaan yang skriptural dan intoleran.
Aji Sofanudin menjelaskan, sebenarnya kuttab sudah ada sejak lama. Di Arab, kuttab sudah ada sebelum Islam, menjadi tempat belajar bahasa, syair, dll. Kemudian di masa Islam kuttab menjadi tempat belajar al-Quran dan agama. Praktiknya, bisa belajar di rumah ustadz, di teras, atau halaman.
“Kemudian sekarang ini kuttab menjadi pendidikan nonformal. Persebarannya ada di Surakarta, Jogjakarta, Tegal. Misalnya Kuttab Al-Fatih, ini memiliki banyak cabang, menjadi brand besar di mana yang lain mengikuti,” kata Aji.
Ambiguitas kuttab, lanjut Aji, adalah pada legalitas atau perizinannya. Sebagian kuttan berizin pada Dinas Pendidikan dengan status pendidikan luar sekolah atau nonformal. Sebagian berizin pada Kemenag di bawah bidang pesantren. Ada juga yang tidak berizin namun menjadi bagian dari PKBM (sekolah formal kejar paket).
“Dari sisi perizinan tidak tepat, kurikulumnya berisi pendidikan agama, mengapa tidak berada di bawah naungan Kemenag. PKBM itu kan kejar paket yang memfasilitasi orang-orang tua atau orang putus sekolah. Sementara kuttab ini kan memang inputnya anak-anak usia belajar , jadi lebih cocok menginduk peda Kemenag,” kata Aji.
Menguatnya Revavalisme Islam
Samidi melihat sekarang ini banyak sekolah muncul dan menjadi persemaian revivalisme Islam. Revivalisme adalah semangat berislam dengan pemahaman keberagaman yang tekstual. Faham kelompok ini cenderung mendikotomikan agama dan negara.
“Di satu sisi orang tua senang, dengan sekolah islam itu anaknya menjadi pandai mengaji, pandai membaca Al-Quran, tetapi di balik itu ada pemahaman agama yang intoleran. Contohnya adalah tidak mau berteman dengan orang beda agama, dengan anggapan berteman dengan orang kafir,” kata Samidi.
Revivalisme Islam ini cukup mengkhawatirkan di tengah kehidupan berbangsa yang majemuk. Sehingga ancaman perpecahan bisa terjadi karena sentimen agama yang terlalu besar.
Pendidikan Object Method
Sementara itu Irwan melihat perkembangan pendidikan Islam yang menjadi primadona di masyarakat. Lembaga pendidikan berlabel islam laku keras, pun biaya tidak murah. Di sini terjadi komodifikasi pendidikan Islam. Namun secara substansi bisa dipertanyakan di tengah munculnya paham-paham intoleran yang justru berkembang dari sekolah.
Menurut Irwan, terjadinya penanaman paham-paham yang intoleran, juga bainwash pemahaman keagamaan, itu karena pendidikan Islam berhenti pada object method. Siswa tidak menjadi subject method, di mana peserta didik hanya dimasuki knowledge yang menyetir pemikiran mereka.
Sekarang ini pendidikan Islam terjadi dekontekstualisasi, yakni lepasnya koteks atau hubungan antara pendidikan dengan masyarakat.
Pandangan yang mengeras sekarang ini bahwa sekolah adalah sumber pengetahuan. Padahal sebenarnya sekolah yang memberitahu atau mentransmisi knowledge kepada sebagian orang, dan yang menerima pengetahuan itu bisa jadi lebih tahu. Sekarang guru dan dosen dianggap yang paling tahu, padahal faktanya masyarakat sudah memiliki knowledge yang dihimpun dari pengalaman historis dalam menjadi kehidupan, menyelesaikan masalah sosial atau masalah alam.
Knowledge masyarakat itu bernama kearifan. Dan sekolah sekarang memutus konteks antara knowledge masyarakat dengan sistem pendidikan yang dijalankan. Apa yang terjadi di luar pagar sekolah tidak terkoneksi dengan sekolah dan ruang kelas di mana-anak belajar.
“Di sinilah sekolah perlu mengkontekstualisasi pengetahuan masyarakat. Sehingga apa yang terjadi di luar sekolah terkoneksi dengan apa yang ada di sekolah,” kata Irwan.
Terkait tumbuhnya pemahaman keagamaan yang intoleran, Irwan menganggap hal itu sebagai produk pendidikan yang oposisional. Yakni memandang dunia secara oposisi atau berlawanan yang membentuk kategori-kategori yang berlawanan pula. Misal istilah muslim dan nonmuslim, ini adalah istilah yang oposisional yang mengarahkan pada pemahaman bahwa kita berlawanan dengan orang lain. (Syafa)
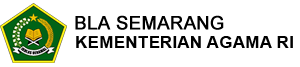



 30 Juli 2018
30 Juli 2018
 7 Mei 2021
7 Mei 2021
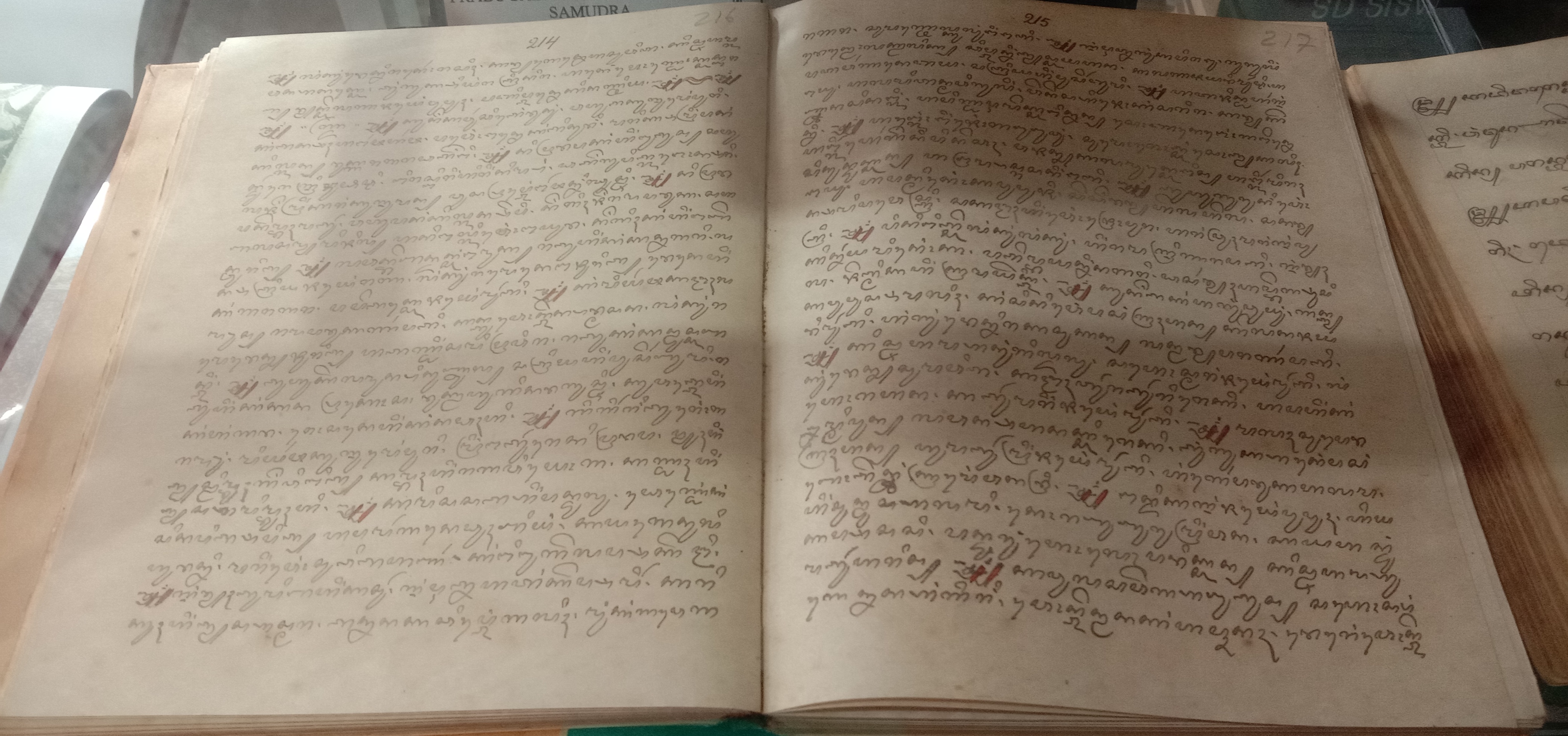 31 Oktober 2020
31 Oktober 2020
 7 Juli 2020
7 Juli 2020